Medan, Film Medan - Ekspektasi terhadap film budaya atau berlatar
budaya yang sempat bertumbuh melalui film “Jandi
La Surong” (2019) hasil karya sineas Sumatera Utara belum lama ini, merupakan modal kuat penulis
untuk menyaksikan “Pariban: Idola dari Tanah Jawa”. Sungguh, proses penggalian
potensi yang dimiliki Sumatera Utara yang punya banyak kebudayaan ini adalah
suatu hal yang membanggakan, khususnya bagi penulis yang jelas asli
kelahiran Sumatera Utara.
Sebenarnya ekspektasi semakin besar melihat
trailer yang disajikan sebelum film ini masuk layar lebar. Dengan durasi dua menit, beberapa lelucon
segar lumayan menggoda untuk disaksikan. Dari sana kemudian pula bisa
dibayangkan ciri humor Sarkas dengan ucapan bapak Moan (Joe Project P) yang
menggambarkan betapa fulgar dan sarkasnya komedi dalam film ini. Kemunculan bintang-bintang
ternama seperti Ganindra Bimo (Headshot), Atikah Hasiholan (Toba Dream, Tiga
Nafas Likas), Rio Dewanto (Filosofi Kopi), dan Rizky Mocil (Love for Sale) juga
memperkuat ekspektasi, plus sebagai pamungkasnya Andibachtiar Yusuf yang mempesona
melalui "Love for Sale" (2018) dan Stayco Media sungguh membuat harga tiket bioskop di
weekend terasa tidak menjadi halangan untuk segera menikmatinya.
Penulis masih terpapar nostalgia serial "Pariban dari Bandung" (1997) yang sangat apik, baik dari karakternya, maupun cara penceritaan oleh Eduart Pesta Sirait kala itu. Siapa yang bisa lupa dengan tingkah Cok Simbara dan romansanya yang dibangun bersama Nella Regar? Dari awal kabar film ini akan diproduksi, penulis sudah melambungkan khayalan mengenai betapa bagusnya film ini nantinya.
Dan malapetaka itu kemudian hadir mulai dari
awal film hingga lima menit pertama. Komedi cerdas dan elegan ala Love for Sale
tiba-tiba hilang tak membekas sedikitpun di film ini. Suguhan gambar demi
gambar bak sineas baru belajar melucu disuguhkan. Hal-hal yang mengganggu fokus penonton di tiap adegan dipaksa sebagai suatu hal yang lucu. Kolase demi kolase, bukan
sebuah kesatuan narasi yang kuat terus dipajang, memaksa penonton masuk ke
dunia yang dihuni Halomoan Brandon Sitorus yang sama sekali tidak menggambarkan ciri seorang keturunan Batak dari Samosir, sungguh pun dari lahir tak pernah pulang ke kampung hlamannya sekalipun. Untungnya kehadiran Mamak Moan yang
berboru Silalahi sedikit meyakinkan, mengingat bahwa kampungnya ada di Samosir.
Tapi sungguh, kehadiran Lina Marpaung alias Mak Gondut di sini lagi-lagi tidak
menguatkan kesan. Rasanya semakin menambah keraguan piala citra tahun 2012 yang
diraihnya melalui “Demi Ucok” (2012). Sebuah ajang FFI yang penuh kontroversi dari
segi nominator maupun pemenangnya. Penulis sudah berusaha memaafkan melalui
film “Luntang Lantung” (2014), dan “Lamaran” (2015), tapi sungguh, tidak ada
sedikitpun perubahan berarti yang dibawakan melalui peranan beliau. Terkesan
hambar dan jauh dari harapan Ibu Batak yang penting dan lucu.
Dalam babak berikutnya, penulis mencoba
mengembalikan semangat menontonnya karena setting film ini kemudian berpindah
ke Tomok! Sebuah tempat yang tak lagi asing bagi penulis. Baik dari perjalanan
melalui Panguruan via Tele, ataupun menerobos membelah Danau Toba melalui
Perapat via Ajibata. Penulis yang penuh percaya diri akan merasa mudah untuk
masuk ke setting itu, sedikit ternganga melihat “Samosir” yang disajikan. Sebuah
kalimat celetukan penulis lontarkan seketika saat adegan demi adegan tentang
Samosir dimunculkan, “Sok tahu!” Paling fatal adalah perjalanan dari rumah Uli
yang jelas terlihat di daerah Pangururan, tiba-tiba berbelanja di Pasar Balige!
Dan pulangnya diajak ke Tomok yang ternyata Batu Persidangan Siallagan di
TukTuk! Astaga! Belum lagi kemunculan adegan pertunjukan di batu persidangan
sebagai bagian dari “acara muda-mudi” Samosir katanya, di malam hari pula!
Hancurnya ekspektasi atas film berlatar budaya
Batak yang benar ini kemudian penulis coba nikmati sebagai film stereotype
kelas rendah melalui lelucon yang disajikan melalui karakter Binsar, Halomoan,
dan keluarga Uli. Berkali-kali penulis mencoba memaafkan ketidaksesuaian ciri orang
Samosir yang dibawakan dalam adegan demi adegan. Plus, ketidakkonsistenan
tingkat “kaya”nya Halomoan yang terlalu “miskin” hingga urusan memiliki
kendaraan di Samosir dan mengganti anjing yang tertabrak saja harus dipaksakan
logis bagi penonton.
Arah dan tujuan setiap karakter yang muncul sedemikian
berantakannya, sehingga membuat hilangnya chemistry antar karakter. Hambar yang
terasa saat penulis mencoba merasakan romansa antara Moan dan Uli, serta
kecerdasan Uli yang tiba-tiba terlihat feminis dengan prinsip pariban yang
dibawanya. Please! Penulis tidak bisa lupa, Uli katanya lulusan luar negeri!
Serpihan makin bertebaran saat memaksakan Bapak Uli (Rukman Rosadi) dan Ibu Uli
(Dayu Wijanto) harus disetujui sebagai bapak dan ibu asli Samosir dengan segala
keluguan dan kampungan ala Samosirnya. Sayang, pembuat film ini semuanya tak
paham bagaimana seharusnya orang-orang Samosir itu ber-adat-nya. Belum apa-apa
seorang Nantulang memeluk berenya tanpa sungkan di depan rumah!
Hingga akhir film, akhirnya kekecewaan terhadap
film ini semakin memuncak. Promosi murahan yang mengajak penonton untuk
mengikuti lanjutan film ini berikutnya nanti layak menjadi cibiran. Tak belajar
dari kasus “Benyamin Biang Kerok” kemarin yang sukses menjadikan suku Betawi
jadi murahan, kali ini sukses pula merendahkan nilai Batak dalam film menjadi sebuah
objek jualan “sekuel” yang dipaksakan. Overall, film ini benar-benar
mengecewakan, tak lebih dari humor dialog sarkas, dan montase berantakan yang
dipaksakan logis sebagai film Batak. (MG)
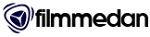


Nice Blog
ReplyDeletePost a Comment